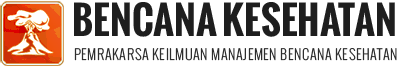Ciamis - Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang rawan bencana alam. Untuk itu, Pemkab Ciamis melakukan apel siaga bencana di Halaman Pendopo Bupati, Senin (29/11/2021).
Unsur yang terlibat antara lain BPBD Ciamis, PMI, TNI-Polri, Tagana, relawan dari Rafi dan Orari. Sejumlah alat berat, kendaraan, armada pemadam kebakaran, ambulans dan penanganan bencana pun dicek dan dipersiapkan.
Selain apel, dilaksanakan juga latihan penanganan bencana longsor dan pohon tumbang. Serta melakukan penanganan penyelamatan terhadap korban bencana agar cepat saat melakukan evakuasi guna mendapat perawatan medis.
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengatakan sejumlah daerah di Kabupaten Ciamis termasuk dalam rawan bencana. Bencana yang sering terjadi di Ciamis adalah tanah longsor dan pergerakan tanah. Selain itu, banjir dan puting beliung kerap melanda sejumlah wilayah di Ciamis.
"Ini kesiapsiagaan kita, latihan ketika menghadapi kejadian bencana alam. Intinya untuk penyelamatan. Dalam penanganan bencana ini tidak hanya pemerintah, tapi semua elemen turut terlibat termasuk masyarakat," katanya.
Herdiat mengatakan menurut prakiraan dari BMKG, kondisi cuaca ekstrem dengan intensitas hujan tinggi terjadi pada Oktober 2021 hingga Februari 2022. Untuk itu kewaspadaan harus ditingkatkan agar saat terjadi bencana bisa langsung dilakukan penanganan cepat.
Kondisi cuaca cukup ekstrem intensitas hujan cukup tinggi. Diperkirakan dari Oktober hingga Februari. "Ciamis masuk salah satu daerah dengan rangking ketujuh dalam kerawanan bencana," ucap Herdiat.
Bupati menyatakan kesiapan sarana dan prasarana secara umum dalam penanganan bencana sudah lengkap. Meski ada beberapa yang kurang dan harus dilengkapi.
"Anggaran juga sudah kami siapkan. Intinya semua pihak harus bahu-membahu menjadi garda terdepan dalam menangani bencana alam," kata Herdiat.