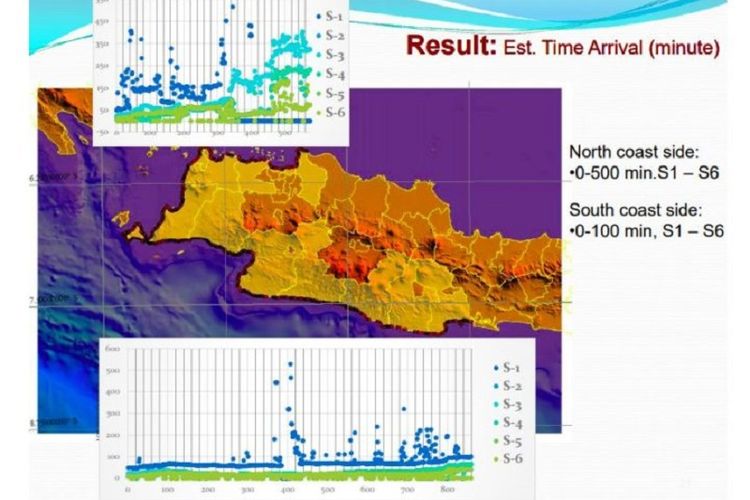
KOMPAS.com - Abdul Muhari, Chairman Sentinel Asia Tsunami Working Group, menanggapi pemberitaan soal gempa megathrust bermagnitudo 8 di Jakarta dan potensi tsunami 57 meter di Pandeglang lewat opininya di Harian Kompas, Selasa (10/04/2018).
Dia menyayangkan pemberitaan tentang kedua hal tersebut hanya fokus pada ancamannya saja, sedangkan solusi dan mitigasinya justru nyaris tak mendapat sorotan. Padahal menurut dia, kajian ilmiah yang dilakukan oleh Widjo Kongko mungkin akan memberi pengaruh baik dalam hal mitigasi, walaupun penyusunannya bukan perkara mudah.
Sebelum menyusun mitigasinya, Abdul menyebut bahwa kita perlu mengetahui terlebih dahulu dua karakteristik bencana terkait gempa dan tsunami. Kedua karakteristik tersebut adalah high frequency but relatively low to medium risk (bencana yang sering terjadi tetapi relatif memiliki dampak risiko kecil sampai medium) dan low frequency but high risk disaster (bencana yang jarang terjadi tetapi memiliki dampak risiko sangat besar). Baca juga: Merencanakan Mitigasi Gempa Jakarta, Apa yang Perlu Diketahui?
"Skenario gempa untuk kasus pertama adalah skenario yang paling mungkin dan paling sering terjadi secara historis dalam membangkitkan tsunami di kawasan tersebut," tulis Abdul.
"Karakteristik jenis ini biasanya memiliki periode ulang pendek sekitar 50 sampai 150 tahun, dengan estimasi tinggi tsunami kurang dari 10 meter," tambahnya. Sementara itu, karakteristik bencana kedua merupakan asumsi skenario terburuk yang mungkin digunakan. "(Mungkin) terjadi secara ilmiah dengan periode ulang lebih dari 400 tahun dan estimasi tinggi tsunami di atas 20 meter (Muhari dkk, 2015)," tulisnya.
Selain mengetahui karakteristik bencana, hal yang menurut Abdul penting bagi mitigasi adalah regulasi. Bencana Risiko Tinggi Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pasal 17 Ayat (1) menyebutkan bahwa mitigasi bencana dengan tingkat risiko tinggi dititikberatkan pada kegiatan non struktur/non fisik. Peraturan ini bukan lahir tanpa sebab.
Berkaca pada pengalaman gempa dan tsunami Jepang tahun 2011 memberikan kita pelajaran yang sangat penting bahwa tidak ada satu struktur fisik yang mampu menahan hantaman tsunami di atas 20 meter.
Selain itu, meski bangunan dilengkapi penahan tsunami, tapi umur struktur fisiknya (beton sekalipun) tidak mungkin melebihi 50 tahun. "Sedangkan ketika kita berbicara tsunami dengan kategori besar, maka kita berbicara periode ulang di atas 400 tahun," ungkap Abdul.
"Artinya, ketika tsunami terjadi, struktur penahan tsunami tersebut mungkin sudah dalam kondisi tidak optimal dalam mereduksi potensi dampak yang mungkin terjadi," tambahnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana upaya non-struktur dalam kasus bencana dengan tingkat risiko tinggi? Menurut Abdul, hal ini dimulai dari tata ruang kawasan pesisir yang berbasis mitigasi.
"Pasca-tsunami tahun 2011, Jepang membagi kawasan pesisir yang direkonstruksi menjadi dua bagian yakni kawasan yang hampir pasti selalu terkena dampak tsunami dengan periode uang 30-150 tahun (berjarak sampai 1 kilometer dari bibir pantai) dan kawasan yang hanya terdampak oleh tsunami dengan periode ulang di atas 200 tahun (berjarak sampai tiga kilometer dari bibir pantai)," katanya.
"Kedua kawasan ini tidak boleh diisi dengan pemukiman," imbuh Abdul. Meski begitu, pemerintah Jepang memperbolehkan kawasan pertama dimanfaatkan untuk pariwisata dan konservasi, sedang kawasan kedua hanya boleh dimanfaatkan oleh industri dan pertanian dengan syarat ketahanan bangunan terhadap gempa dan tsunami yang sangat ketat.
Selain itu, prasarana evakuasi dari tsunami juga harus tersedia dan mudah dijangkau bagi pengguna kawasan ini. "Untuk kawasan yang belum terjadi tsunami dengan pemukiman di kawasan pesisir sudah relatif sangat padat, edukasi dan pelatihan evakuasi yang ditunjang dengan ketersediaan prasarana tempat evakuasi yang mudah dicapai adalah hal utama," kata Abdul.
"Jepang melakukan gladi evakuasi di tiap kota yang rawan tsunami setidaknya tiga kali dalam setahun," imbuhnya. Tak hanya itu, menurut Abdul, untuk melindungi aset ekonomi seperti bangunan dan infrastruktur yang dibangun di kawasan rawan tsunami, peran serta asuransi dalam manajemen risiko sudah tidak bisa ditunda.
"Regulasi nasional mengenai asuransi bencana mendesak untuk diadakan.Tanpa adanya regulasi nasional, skema asuransi bencana di Indonesia sulit diwujudkan. Baca juga: Tanpa Buoy, Seberapa Akurat Sistem Peringatan Dini Tsunami Kita? Bencana Risiko Sedang Berbeda dengan bencana risiko tinggi, untuk jenis bencana dengan tingkat risiko sedang dan kecil, Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 yang digunakan.
Peraturan ini berisi tentang Mitigasi Bencana di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pasal 17 Ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa fungsi struktur fisik bisa dikedepankan ditunjang dengan upaya non-fisik. Peraturan ini dimaksudkan agar keberadaan struktur fisik berupa (misalnya) hutan pantai, tanggul dan pemecah gelombang dapat seiring sejalan dengan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam merespons tanda-tanda bahaya seperti peringatan dini, gejala alam dan lain-lain.
Di samping semua itu, menurut Abdul, informasi tentang kebencanaan perlu dipahami dalam arti yang lebih luas. "Suatu hasil kajian boleh saja diperdebatkan, imbauan agar masyarakat tetap tenang dan waspada boleh saja dilakukan," kata Abdul. "Akan tetapi hal tersebut harus dibarengi dengan tindakan yang lebih mendesak yakni implementasi upaya mitigasi baik struktural maupun non-struktural yang direncanakan dengan baik dan tersosialisasikan secara berkelanjutan kepada masyarakat," tegasnya.
sumber: https://sains.kompas.com

