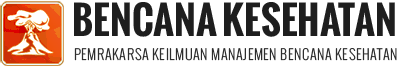Merdeka.com - Banjir di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh menyebabkan 128 keluarga terdampak. Selain itu puluhan rumah terendam banjir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Simeulue Zulfadli mengatakan, korban terdampak tersebut merupakan warga Desa Leubang Hulu, Kecamatan Teupah Barat.
"Hujan lebat yang terjadi sejak beberapa hari terakhir menyebabkan puluhan rumah di Desa Leubang Hulu, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue direndam banjir. Sebanyak 128 keluarga terdampak bencana tersebut," kata Zulfadli. Minggu (18/12). Dikutip dari Antara.
Ketinggian banjir yang melanda wilayah tersebut mencapai 80 sentimeter. Banjir tidak hanya merendam rumah penduduk, tetapi juga fasilitas umum seperti sekolah, masjid dan badan jalan.
"Banjir juga merendam persawahan dan perkebunan serta memutuskan akses warga dari dan ke daerah tersebut. Hingga kini, belum ada warga yang mengungsi. Warga masih bertahan di rumah masing-masing," lanjutnya.
Selain di Desa Leubang Hulu, kata Zulfadli, banjir juga terjadi di Desa Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue. Banjir merendam jalan raya hingga tidak dapat dilewati.
"Untuk membantu warga melintas, tim BPBD Simeulue dibantu pihak terkait menyediakan perahu karet. Selain itu, warga desa membuat rakit membantu masyarakat yang melintas," terangnya.
Zulfadli mengatakan tim BPBD Kabupaten Simeulue juga sudah diturunkan ke lokasi banjir untuk menyalurkan bantuan, mendata masyarakat terdampak, serta menilai kerugian akibat musibah ini.
"Tim juga bersiaga membantu masyarakat yang membutuhkan evakuasi. Kami juga sudah menyiapkan kebutuhan masa panik seperti dapur umum, dan tenda pengungsian," bebernya.
BPBD mengimbau masyarakat di Kabupaten Simeulue mewaspadai cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan bencana alam.
"Berdasarkan peringatan dini BMKG, ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat dan angin kencang di beberapa wilayah di Kabupaten Simeulue hingga beberapa hari ke depan," tandasnya.