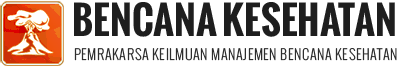Notulensi INDO HCF Expert Meeting:
Mewujudkan SPGDT-S dan SPGDT-B Terintegrasi Pra, Intra dan Inter Hospital Secara Nasional
Jakarta. INDO HCF menyelenggarakan expert meeting pada 1 Desember 2016, forum ini telah lama menggerakkan banyak diskusi terkait kegawatdaruratan. Kali ini, INDO HCF mengundang para ahli dari bidang terkait, yaitu Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SpB, SpOT; Prof. Dr. dr. Aryono D Pusponegoro Sp. B (K)-BD, FINACS, FRCS (Ed); dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD; David Handojo Muljono, MD, Sp.PD, FINASIM, Ph.D, serta dr. Tri Hesty Widyastoeti Marwotosoeko, Sp.M (Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes). Pertemuan ini bukan yang pertama, upaya INDO HCF untuk concern terhadap isu kesehatan telah dilakukan berulang kali, antara lain: penelitian terkait pelayanan JKN di puskesmas (KIA), serial diskusi panel JKN, isu strategis, serta berbagai penelitian dan pelatihan yang terkait bidang tersebut.
Faktanya, hingga saat ini banyak pakar di bidang kesehatan tetapi tidak bisa dimanfaatkan di daerah.
Ide terlaksananya expert meeting kali ini ialah bagaimana menurunkan angka emergensi di Indonesia. Menurut WHO dalam kematian akibat lalu lintas nomor 3, setelah Tiongkok dan India. Harapannya, forum semaca ini dapat mengumpulkan komunitas terkait, diskusi bersama dan akhirnya saling terinformasikan. Masalah utama dalam penanganan bencana ialah tidak ada info tenaga medis yang akurat, tegas dr. Supriyantoro (Ketua INDO HCF) dalam sambutannya. Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan di tingkat masyarakat dan hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Tema yang diambil kali ini yaitu SPGDT yang harapannya bukan hanya membentuk call center. Masih muncul pula isu dalam rujukan, seharusnya ini menjadi tanggung jawab RS, merujuk, menginformasikan keadaan dan mengirim pasien. Pernyataan dari Supri ialah perlukah ada wadah untuk merumuskan banyak hal untuk kebijakan-kebijakan RS.
Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementrian Kesehatan RI menyatakan, dalam manajemen bencana kita tidak ada manajemen resiko yang benar-benar baik. Dalam pemaparannya terkait Kebijakan Pemerintah dalam Pemerintah SPGDT-S dan SPGDT-B, harapannya dalam penanganan korban dapat mempercepat waktu penanganan korban. Kita harus banyak mencontoh pengalaman Tokyo, yang dapat mengirim ambulans maksimal 10 menit sejak dipanggil. Hal ini sudah ditiru Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Tulungagung yang tidak banyak mengalami kemacetan.
Public safe center wajib dibentuk di seluruh daerah, di 540 kabupaten namun baru127 yang terhubung dengan call center 119. Latar belakang pentingnya SPGDT:
-
Berubahnya pola penyakit (kecelakaan menduduki urutan ke-2 saat ini)
-
Meminimalisir kecacatan atau kematian.
Kemenkes membutuhkan masukan dari pakar dan asosiasi profesi. Masukan untuk masalah terkait pasien dapat disampaikan ke bagian layanan kesehatan (yankes) dan khusus untuk masalah terkait bencana dapat disampaikan ke Pusat Krisis Kesehatan (PKK) baru ke yankes.
dr. Hendro Wartatmo, Sp. BD (FK UGM) menyatakan SPGDT sudah dimulai sejak terbitnya peraturan Sekjen pada 2003. Pada periode 1996-2004, SPGDT dijalankan melalui Pusbankes 118 PERSI DIY. SPGDT merupakan perpaduan antara unit-unit pelayanan kesehatan. Sementara, call center adalah konsekuensi logis, bagian dari komponen saja. Nama awal SPGDT ialah Deklarasi Makkasar tahun 2000, mama kedua yaitu Brigade Kesehatan Bencana. Pengalaman Hendro, Tim Bantuan Bencana UGM mendarat di Meulaboh, pasca tsunami, menumpang pesawat Mensos saat itu. Tim pertama berangkat, iuran dari kantong pribadi. Jika sudah ada sistem, pemberangkatan tidak sulit, terang Hendro. Kemudian, program ini dilanjutkan hingga 2 tahun dan dinamai Aceh Supporting Program dan di-back-up oleh FK UGM serta RS Sardjito.
Saat ini tim Pokja Bencana UGM mengembangkan secara teknis dan manajemen. Manajemen bencana telah menjadi intrakurikuler di FK UGM di program S1 dan S2. Hendro juga menjadi anggota World Association Disaster and Management (WADEM) agar dapat terus berkontribusi pada upaya penanganan dan manajemen bencana di Indonesia. Hendro memaparkan seharusnya insider commander berasal dari BNPB.
David Handojo Muljono, MD, Sp.PD, FINASIM, Ph.D (FK Univ. Hasanudin) memaparkan “Memasyarakatkan SPGDT sehari-hari dan efisien”. Handojo menyatakan masih banyak praktek membawa pasien ke RS dengan kendaraan umum/pribadi. Sayangnya baru 4,7% dari seluruh daerah di Indonesia yang memiliki layanan gawat darurat. Sebaiknya ada pelatihan yang diinisiasi pemerintah, agar terjadi keterpaduan antara pemerintah dan masayarakat dalam kegawatdaruratan,
Prof. Dr. dr. Aryono D Pusponegoro Sp. B (K)-BD, FINACS, FRCS (Ed) memaparkan “Kontroversi dalam penanggulangan kegawatdaruratan”. Salah satu fakta yang menjadi kontroversi ialah di beberapa daerah call center tidak bisa ditelpon karena listrik mati. Aryono berpendapat komandan dalam penanganan bencana atau insider commander sebaiknya polisi sebagai komandannya, karena ia memiliki fungsi secara law and order. Untuk setiap daerah/kota harus membentuk public safety center, ada polisi, ambulans dan damkar.
Pengalaman di lapangan. pasca bom Bali 1, Aryono berhasil melatih 3000 pecalang, sehingga saat bom Bali 2 pecalang. Menurut Aryono, triase harus dilatihkan ke pihak pengamanan hotel jika ada ancaman kecelakaan/bencana di sekitar hotel. Poin yang dapat disimpulkan, sejauh ini tenaga penanganan bencana di Indonesia masih not well organized dan not well trained.
Beberapa poin penting. Pertama perlu dipikirkan juga untuk evakuasi korban di daerah terpencil dan perbatasan, bagaimana sistemnya. Kedua, pelibatan masyarakat selalu bisa coba dilakukan, seperti di Jatim yang telah terbentuk Forum Pengurangan Bencana. Di Sleman, saat erupsi stakeholder berhasil menggerakkan komunitas melalui Jalin Merapi (radio komunitas). Selain itu, perlu tokoh dari pemerintah yang mau terjun memimpin, seperti di negara tetangga, Malaysia, Wakil Perdana Menteri yang langsung mengkoordinir setiap kasus emergensi bencana nasional. Ketiga, permintaan dari peserta yaitu BNPB ialah pemerintah tergerak untuk menyusun pelatihan agar Tim Reaksi Cepat diberi pelatihan yang akan bermanfaat di lapangan. Sayangnya sudah ada BPBD daerah yang memiliki ambulans, namun tidak ada paramedisnya. Keempat, kelemahan dalam penanganan bencana ialah sistem dan integrasi yang belum kuat. Tantangan ke depan ialah pengembangan flying healthcare untuk menjawab kebutuhan di pulau-pulau yang terisolasi atau sulit dijangkau melalui transportasi darat. Prof Idrus menambahkan, ke depan, perlu dilakukan pengorganisasian relawan (W).
![]() Materi Presentasi
Materi Presentasi